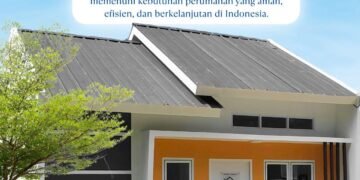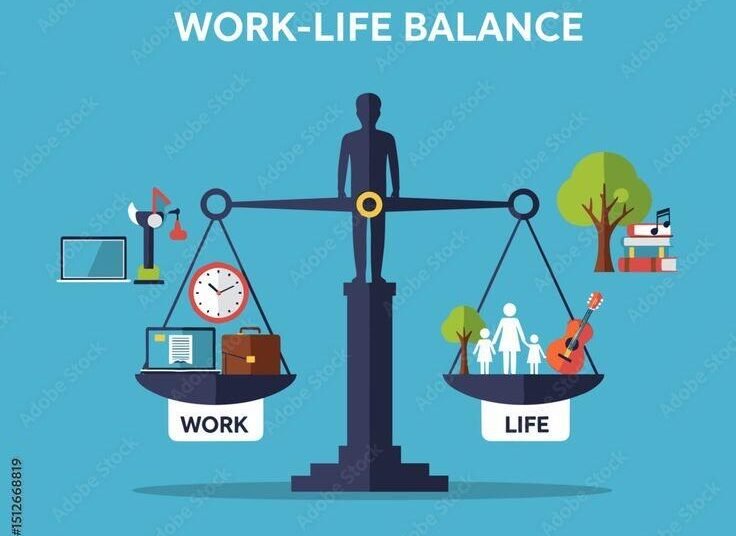Dari Work-Life Balance hingga Digital Mindset: Apa Sih Ekspektasi Gen Z terhadap Manajemen SDM?
Kini hampir 30% tenaga kerja di Indonesia berasal dari Generasi Z, mereka yang lahir antara tahun 1997–2012. Tumbuh dalam era internet dan media sosial, kehadiran mereka menghadirkan warna baru sekaligus tantangan serius bagi dunia kerja. Jika dulu bekerja identik dengan stabilitas, gaji bulanan, dan jam kantor panjang, bagi Gen Z itu tidak lagi cukup. Mereka menuntut lebih luas untuk keseimbangan hidup yang nyata, fleksibilitas, ruang untuk berkembang, hingga budaya kerja yang ringan serta digital. Pertanyaannya adalah siapkah manajemen SDM menjawab ekspektasi ini?
Bagi Gen Z, menyeimbangkan kehidupan dan pekerjaan bukan sekadar omongan belaka tapi kebutuhan utama. Mereka tidak lagi menilai produktivitas dari lamanya duduk di kantor, melainkan dari hasil yang dicapai. Survei Deloitte 2023 bahkan menunjukkan bahwa work-life balance menjadi pertimbangan utama dalam memilih pekerjaan oleh 46% Gen Z di Asia Tenggara. Kenyataan di lapangan tampak jelas di perusahaan seperti Google dan Gojek yang sudah menerapkan fleksibilitas kerja dan layanan kesehatan mental. Di sisi lain, banyak perusahaan tradisional masih memaksakan jam kerja panjang, hal ini kerap disuarakan di media sosial. Seorang pengguna menulis di platform X, “Gaji besar tidak ada artinya kalau jam kerja sampai larut malam dan tidak ada waktu untuk diri sendiri.” Ungkapan sederhana itu viral karena menyuarakan kegelisahan banyak anak muda. Teori Herzberg (1959) melalui Two Factor Theory menjelaskan bahwa kepuasan kerja bukan hanya dipengaruhi oleh gaji atau fasilitas, melainkan juga faktor motivator seperti fleksibilitas, pengakuan, dan ruang berkembang. Greenhaus dan Powell (2006) menambahkan bahwa keseimbangan hidup justru meningkatkan produktivitas, bukan menguranginya.
Pertama, sebagai digital native, Gen Z melihat kehidupan kerja melalui lensa teknologi. Dimana sistem manual dianggap kuno. Proses rekrutmen via online, absensi di aplikasi, hingga pelatihan lewat e-learning adalah standar minimum. Fenomena ini terlihat jelas di sektor perbankan digital seperti Jago dan SeaBank menarik minat Gen Z karena efisien dan transparan, sementara bank konvensional yang birokratis mulai ditinggalkan. Banyak karyawan muda di Instagram dan LinkedIn membandingkan pengalaman mereka antara bekerja di perusahaan “melek digital” dengan yang kaku. Konsep dari Davis “Technology Acceptance Model” memang menekankan bahwa adopsi teknologi sangat bergantung pada persepsi kemanfaatan dan kemudahan. Peter Drucker bahkan pernah mengingatkan bahwa organisasi yang tidak berubah jadi knowledge-based akan tertinggal.
Kedua, Gen Z juga mencari makna dalam pekerjaan, bukan sekadar jabatan atau gaji tinggi. Mereka ingin merasakan dampak positif, tidak hanya untuk diri mereka tapi juga bagi masyarakat. Itulah mengapa banyak dari mereka memilih perusahaan seperti Unilever dan Danone yang memiliki program keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Di platform TikTok, fenomena resign meski gaji tinggi lalu memilih startup kecil yang memberi ruang bermakna sering dibagikan. Deci dan Ryan melalui Self-Determination Theory menunjukkan bahwa motivasi intrinsik bertahan lebih lama dibanding eksternal. Sementara Simon Sinek menegaskan bahwa loyalitas datang kepada organisasi yang memiliki “why” yang kuat.
Ketiga, budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif juga penting bagi Gen Z. Mereka menolak budaya kerja kaku dan hierarki yang mengekang kreativitas. Tokopedia dan Ruangguru menjadi contoh budaya egaliter di mana ide dari siapa pun dihargai tanpa tergantung jabatan. Di platform X, karyawan startup sering mencuit, “meski startup lebih berisiko, setidaknya suara kami didengar, tidak hanya disuruh ikut aturan tanpa diskusi.” Edgar Schein menjelaskan bahwa nilai dan norma organisasi membentuk perilaku karyawan, sementara Hofstede menekankan bahwa generasi dengan low power distance lebih nyaman dalam budaya yang egaliter.
Tidak semua suara di media sosial bernada positif. Bulan Agustus 2025, video seorang pegawai Gen Z yang menolak tetap lembur karena sudah menyelesaikan jam kerjanya mendadak viral. Ia berkata, “Bekerja untuk makan, tapi kalau tidak bisa makan dengan tenang, apa artinya? Glorifying struggle is not something to be proud of.” Video tersebut ditonton jutaan kali dan memicu debat sengit, dimana ada yang mendukung ketegasannya, ada pula yang menilai ia kurang memahami realitas kerja keras. Tren tagar #KaburAjaDulu yang sempat viral di platform X juga memperlihatkan bagaimana banyak anak muda mengekspresikan keinginan mencari peluang di luar negeri, bukan semata lari dari tanggung jawab, tetapi sebagai upaya menemukan peluang hidup yang lebih baik.
Ekspektasi Gen Z membuat peran HR tidak lagi sebatas mengurus administrasi, melainkan harus menjadi arsitek budaya kerja. HR dituntut untuk menghadirkan fleksibilitas, mendigitalisasi sistem, membangun jalur karier yang jelas, dan menciptakan lingkungan inklusif. Transformasi ini bukan hanya demi memanjakan generasi muda, melainkan membangun ekosistem kerja yang relevan dengan perkembangan zaman.
Menurut penulis, ekspektasi Gen Z harus dipandang sebagai peluang, bukan beban. Generasi ini memang sering dicap cepat bosan, keras kepala, atau terlalu menuntut, namun di balik itu mereka sedang mengajarkan bahwa dunia kerja tidak boleh lagi berjalan dengan pola lama yang kaku. Kesadaran mereka terhadap pentingnya work-life balance, pemanfaatan teknologi, pencarian makna, serta keberagaman dan inklusivitas adalah tanda bahwa arah dunia kerja sedang bergerak ke masa depan yang lebih sehat. Jika perusahaan gagal merespons, Gen Z tidak segan pergi mencari tempat lain yang lebih sesuai dengan nilai mereka. Namun bila perusahaan mampu beradaptasi, maka bukan hanya Gen Z yang diuntungkan, melainkan juga tercipta ekosistem kerja yang lebih inovatif, berkelanjutan, dan manusiawi. HR bukan lagi sekadar pengurus administrasi, melainkan penggerak perubahan budaya kerja, dan inilah momentum terbaik untuk membuktikan bahwa dunia kerja mampu mengikuti ritme zaman.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”