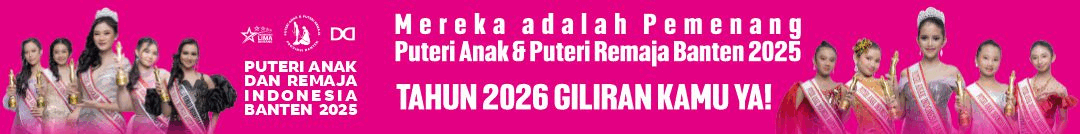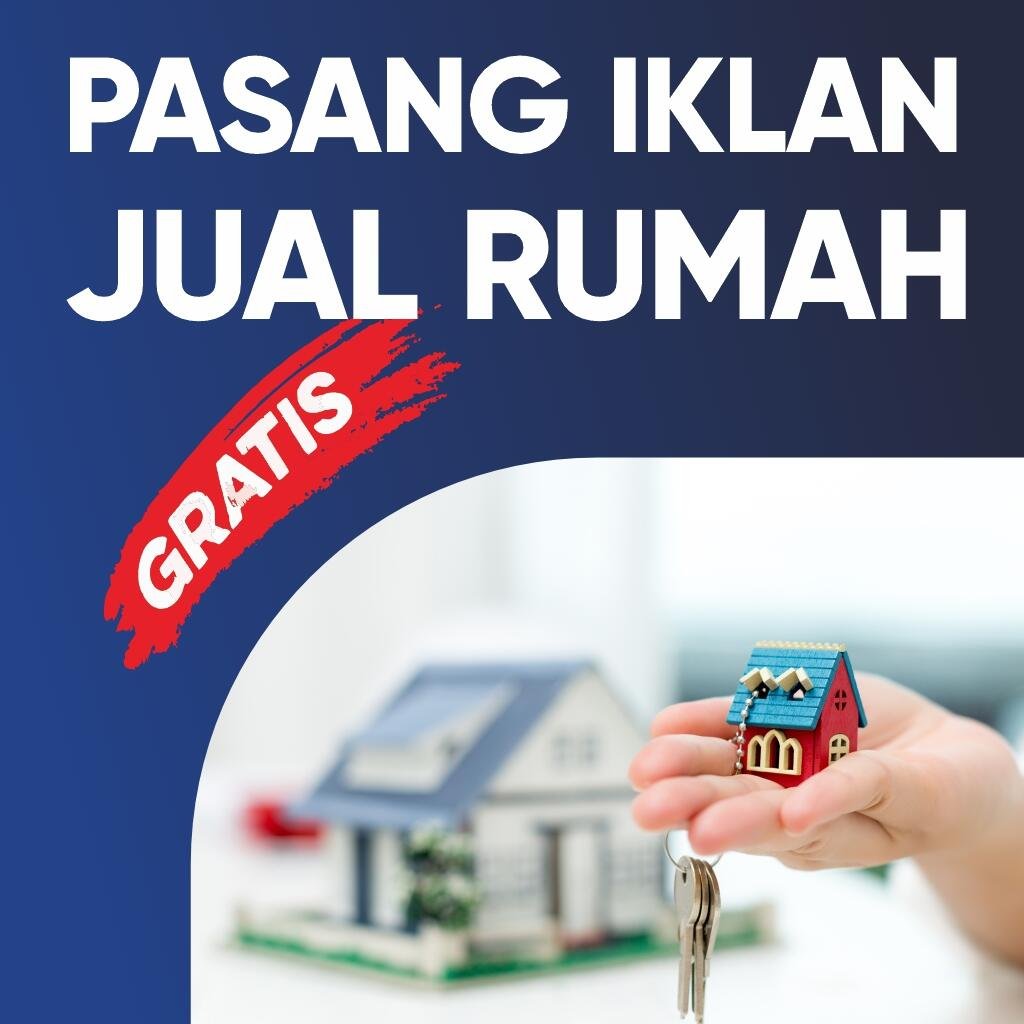Dari Makan Bergizi ke Politik Populisme: Kritik PMII terhadap Politisasi Program MBG di Indonesia
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan pemerintah dengan semangat luhur untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Fokusnya sederhana: menekan angka stunting, memperbaiki gizi anak-anak dan ibu hamil, serta mendorong pemerataan kesejahteraan menuju Indonesia Emas 2045. Namun di balik narasi kemanusiaan itu, terselip dinamika politik yang tidak bisa diabaikan. Program MBG bukan hanya kebijakan sosial, tapi juga arena pertarungan kepentingan antara idealisme kesejahteraan dan pragmatisme kekuasaan. Di titik inilah muncul perlawanan moral dari mahasiswa, salah satunya PMII Kuningan, yang turun ke jalan menolak politisasi MBG. Gerakan itu menjadi pengingat bahwa politik tidak boleh kehilangan nilai etikanya.
Dalam teori politik, populisme sering dipahami sebagai strategi elite untuk meraih legitimasi lewat janji-janji kesejahteraan instan. Ernesto Laclau menyebut populisme sebagai upaya membangun narasi “rakyat” yang dimobilisasi demi kepentingan politik tertentu. Fenomena MBG dapat dibaca dalam kerangka ini: gagasan yang tampak pro-rakyat, namun implementasinya justru sarat kepentingan elektoral. Ketika kebijakan sosial dijalankan tanpa kesiapan sistem dan pengawasan yang kuat, maka yang terjadi bukanlah pemerataan kesejahteraan, melainkan pemborosan politik. Dugaan adanya “jatah dapur” bagi politisi lokal dan praktik rente dalam distribusi proyek MBG memperkuat kesan bahwa program ini rawan dijadikan komoditas politik.
PMII Kuningan memandang bahwa politik populis seperti ini berpotensi menipu kesadaran publik. Mereka menilai program MBG, yang seharusnya menjadi wujud kehadiran negara, justru berisiko menjadi alat pencitraan bagi elite tertentu. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh PMII Kuningan merupakan ekspresi dari kesadaran kritis bahwa kesejahteraan rakyat tidak boleh menjadi barang dagangan politik. Dalam orasinya, mereka menegaskan bahwa bantuan sosial harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan keadilan, bukan dikendalikan oleh logika elektoral. Mahasiswa hadir bukan untuk menolak programnya, melainkan menolak niat buruk di balik kebijakan yang seharusnya murni untuk kepentingan publik.
Di sisi lain, PMII juga memahami bahwa kebijakan sosial adalah salah satu pilar penting dalam sistem welfare state. Namun ketika pelaksanaannya dipenuhi intervensi politik, maknanya bergeser. Welfare state yang seharusnya berpihak pada rakyat kecil berubah menjadi patronage state, di mana bantuan hanya mengalir kepada kelompok yang dekat dengan kekuasaan. Dalam konteks MBG, ini tampak dari carut-marutnya pengawasan, infrastruktur dapur yang belum siap, hingga munculnya kasus keracunan di beberapa daerah. Semua itu memperlihatkan bahwa niat baik tanpa tata kelola yang bersih justru membuka ruang bagi penyimpangan.
Gerakan PMII Kuningan memperlihatkan peran mahasiswa sebagai moral force—penjaga etika di tengah krisis moral politik. Mereka tidak sekadar menolak, tetapi menawarkan kesadaran baru bahwa kesejahteraan rakyat harus dibangun dengan prinsip partisipasi dan akuntabilitas. Dalam konteks demokrasi, mahasiswa adalah penjaga ruang publik agar kebijakan sosial tidak dikooptasi oleh kepentingan segelintir elite. Ketika suara mahasiswa dibungkam, maka demokrasi kehilangan penyeimbangnya. Karena itu, aksi PMII bukan sekadar bentuk penolakan, tetapi bagian dari pendidikan politik yang menumbuhkan kesadaran rakyat terhadap hak-haknya.
Fenomena MBG juga membuka diskursus baru tentang bagaimana politik kesejahteraan di Indonesia masih dibayangi logika transaksional. Pemerintah seolah hadir sebagai dermawan, bukan sebagai pelaksana amanah rakyat. Padahal, dalam pandangan politik Islam dan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi landasan PMII, kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk memperkaya diri atau kelompok. Keadilan sosial hanya bisa ditegakkan jika kebijakan publik berangkat dari niat ikhlas dan berpihak pada yang lemah. Politik yang kehilangan nilai moralnya pada akhirnya hanya menghasilkan kebijakan yang rapuh, dangkal, dan tidak berkelanjutan.
Gerakan mahasiswa seperti PMII Kuningan adalah bukti bahwa idealisme belum mati. Mereka menolak tunduk pada pragmatisme politik yang menipu rakyat dengan simbol-simbol kesejahteraan semu. Mereka hadir sebagai suara nurani, mengingatkan bahwa negara tidak boleh memperlakukan rakyatnya sebagai objek politik. Dalam konteks ini, aksi PMII juga menjadi ajakan bagi generasi muda untuk membangun politik baru—politik yang berpijak pada etika, empati, dan keadilan. Mahasiswa tidak hanya mengkritik, tapi juga membangun narasi alternatif bahwa kesejahteraan sejati lahir dari integritas, bukan dari janji kosong kekuasaan.
Kasus MBG seharusnya menjadi momentum refleksi nasional: apakah negara benar-benar berpihak pada rakyat, atau hanya menjadikan rakyat sebagai alat legitimasi politik? Politisasi bantuan publik adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan penghancuran moral kebangsaan. Di tengah situasi ini, PMII menunjukkan bahwa mahasiswa masih punya nyali untuk bersuara, mengingatkan bahwa politik sejati adalah sarana memperjuangkan keadilan sosial sebagaimana cita-cita konstitusi. Dalam semangat Dzikir, Fikir, dan Amal Sholeh, perjuangan mahasiswa bukan sekadar reaksi, tapi bagian dari jihad intelektual untuk mengembalikan politik pada fitrahnya: melayani manusia, bukan memperalatnya.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”