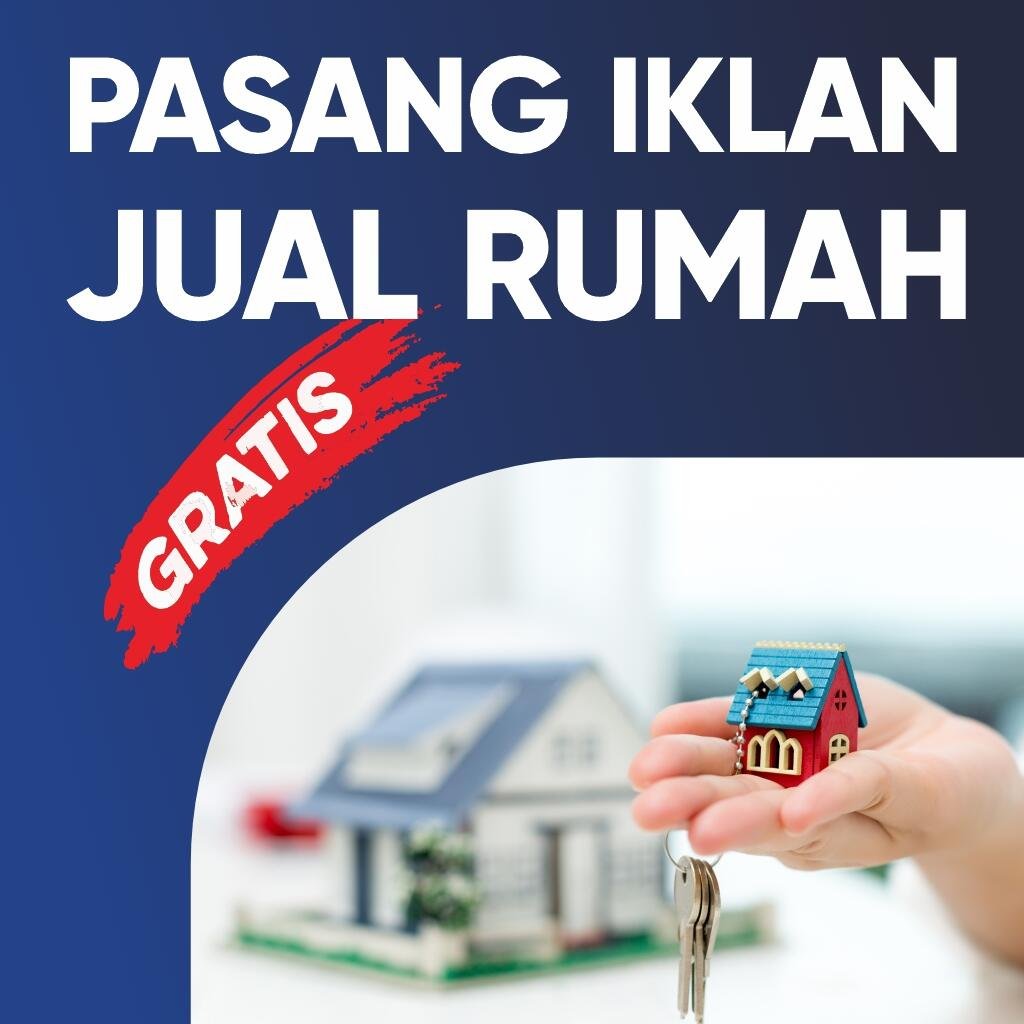Beberapa bulan terakhir, berita tentang masyarakat yang tiba-tiba disetop oleh orang tak dikenal di jalan kembali ramai. Mereka mengaku sebagai debt collector dan menuduh kendaraan korban memiliki tunggakan kredit. Dalam banyak kasus, motor bahkan langsung dirampas di tempat. Padahal, sebagian besar korban bukan debitur bermasalah, mereka hanya kebetulan membawa kendaraan bekas kredit atau bahkan tak punya hubungan apa pun dengan leasing. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting: mengapa praktik ekonomi bisa berubah menjadi bentuk kekerasan di ruang publik?
Kasus semacam ini bukan hal baru. Sejak 2022, Kepolisian RI mencatat peningkatan laporan masyarakat terkait penipuan yang melibatkan oknum debt collector palsu sebesar 23 persen (Kompas, 2024). Para pelaku kerap memanfaatkan celah lemahnya literasi hukum dan ketimpangan sosial di masyarakat. Mereka tahu, sebagian besar warga akan memilih diam daripada melawan, karena merasa “tidak punya kuasa.” Di sinilah wajah gelap ekonomi perkotaan muncul: kekuasaan bukan lagi di tangan negara atau hukum, tapi di tangan mereka yang berani menakut-nakuti.
Fenomena ini menunjukkan bahwa ekonomi tidak lagi sekadar soal transaksi atau kontrak, tapi juga tentang siapa yang berhak memegang kendali atas rasa aman di ruang sosial. Dalam konteks ini, praktik debt collector palsu mencerminkan ekonomi yang telah kehilangan nilai sosialnya, terlepas dari norma moral dan keadilan yang seharusnya menahan perilaku ekonomi agar tetap manusiawi. Granovetter (1985) dalam teori embeddedness-nya menegaskan bahwa tindakan ekonomi selalu tertanam dalam jaringan sosial dan hubungan antarindividu. Artinya, ekonomi idealnya tidak boleh berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan konteks sosialnya. Namun yang terjadi di jalanan justru sebaliknya: ekonomi yang seharusnya tertanam kini tercerabut dari akar moralnya.
Sistem kredit yang masif di Indonesia ikut berperan dalam menciptakan ruang abu-abu bagi praktik ini. Data OJK (2024) menunjukkan lebih dari 100 juta kontrak pembiayaan aktif di sektor kendaraan bermotor, dengan nilai outstanding mencapai Rp500 triliun. Di balik angka itu, ada jutaan masyarakat kelas menengah bawah yang mengandalkan skema kredit untuk bisa memiliki kendaraan. Bagi banyak rumah tangga, motor bukan lagi sekadar alat mobilitas, melainkan simbol status dan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Kredit yang pada awalnya berfungsi sebagai alat mobilitas sosial kini berubah menjadi sumber kecemasan. Keterlambatan cicilan sebulan saja bisa menjadi ancaman, bukan hanya karena risiko kehilangan barang, tapi juga karena hadirnya para penagih yang sering kali lebih ganas daripada hukum itu sendiri.
Yang lebih ironis, sebagian dari mereka yang menjadi debt collector ilegal juga berasal dari lapisan masyarakat yang sama, mereka yang hidup dalam tekanan ekonomi, tanpa pekerjaan tetap, dan mudah tergoda oleh uang cepat. Ini adalah potret ekonomi yang memakan dirinya sendiri. Ketimpangan dan keterdesakan ekonomi melahirkan praktik kekerasan yang kemudian ditujukan kepada sesama kelas bawah. Dalam istilah Pierre Bourdieu (1998), hal ini bisa dibaca sebagai bentuk violence symbolique, kekerasan yang dilegitimasi oleh sistem sosial, di mana yang tertindas justru dipaksa menindas sesamanya demi bertahan hidup.
Di sisi lain, negara terlihat gagap. Pemerintah memang telah menetapkan aturan bahwa penagihan hanya boleh dilakukan oleh pihak yang memiliki sertifikat profesi dan surat tugas resmi. Tapi di lapangan, realitas sosial jauh lebih kompleks. Pelaku ilegal sering menyamar dengan atribut leasing dan surat tugas palsu, sementara masyarakat tidak tahu bagaimana membedakannya. Penegakan hukum yang lemah membuat pelaku bergerak bebas, dan rasa takut masyarakat tumbuh menjadi kebiasaan sosial baru: lebih baik menghindar ketimbang melawan. Inilah titik di mana ekonomi mulai mengatur perilaku sosial melalui rasa takut.
Jika dilihat dari kacamata sosiologi ekonomi, fenomena ini menggambarkan bagaimana pasar dan kekuasaan ekonomi bisa menembus ruang sosial paling intim, ruang publik, jalan raya, bahkan hubungan antarwarga. Karl Polanyi (1944) menyebut proses ini sebagai disembedding, ketika ekonomi tidak lagi diatur oleh norma sosial melainkan oleh mekanisme pasar dan kepentingan kapital. Dalam konteks Indonesia, mekanisme ini diperkuat oleh lemahnya perlindungan konsumen dan ketimpangan ekonomi yang semakin tajam. Masyarakat bawah hidup dalam tekanan utang, sementara regulasi hanya melindungi mereka yang punya akses terhadap hukum dan lembaga formal.
Yang lebih mengkhawatirkan, praktik seperti ini perlahan menormalisasi kekerasan dalam interaksi ekonomi. Ketika seseorang ditodong di jalan atas nama “utang,” dan masyarakat menanggapinya sebagai hal biasa, itu artinya nilai moral dalam ekonomi sudah mulai luntur. Masyarakat kita, tanpa sadar, mulai menerima bahwa ancaman bisa menjadi bagian dari sistem ekonomi. Ini bukan lagi sekadar urusan penipuan, tapi juga masalah moral ekonomi, bagaimana nilai keadilan, empati, dan rasa aman digantikan oleh logika transaksional.
Namun, fenomena ini juga membuka peluang refleksi yang lebih dalam. Jika ekonomi memang selalu tertanam dalam struktur sosial, maka penyelesaiannya tidak bisa hanya lewat aparat atau regulasi. Ia butuh pemulihan moral publik. Butuh kesadaran kolektif bahwa ekonomi bukan sekadar urusan individu, tapi ruang bersama yang seharusnya menegakkan keadilan. Ketika seseorang bisa kehilangan motor di tengah jalan tanpa dasar hukum, itu bukan hanya kegagalan individu, tapi kegagalan negara melindungi warga dan kegagalan masyarakat menegakkan norma sosial.
Pemberantasan debt collector palsu seharusnya tidak hanya dilihat sebagai upaya hukum, melainkan juga sebagai koreksi terhadap cara kita memahami ekonomi. Sebab di balik setiap aksi penipuan atau kekerasan, ada struktur ekonomi yang timpang dan sistem sosial yang membiarkan orang miskin saling menindas. Jika kita terus memisahkan ekonomi dari moralitas, maka kekerasan ekonomi semacam ini akan terus menemukan bentuk barunya: dari leasing ke pinjaman online, dari ancaman di jalan ke ancaman di layar ponsel.
REFERENSI
Bourdieu, P. (1998). Practical Reason: On the Theory of Action. Stanford University Press.
Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology, 91(3), 481–510.
Kompas. (2024, March 11). Maraknya Penipuan Debt Collector Palsu di Jakarta, Polisi Ingatkan Masyarakat Waspada. https://www.kompas.com/
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). Laporan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Tahun 2023. https://www.ojk.go.id/
Polanyi, K. (1944). The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Beacon Press.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”