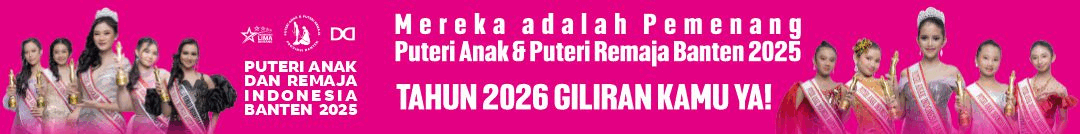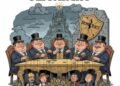Pandemi pernah mengubah cara kita bekerja. Kantor-kantor sepi, ruang rapat pindah ke layar Zoom, dan istilah “work from home” (WFH) menjadi bagian dari kosakata sehari-hari. Kini, ketika aktivitas sudah kembali normal, warisan itu masih terasa. Banyak perusahaan menerapkan model hibrida, sebagian pekerja memilih jalur “remote work” penuh, dan budaya kerja tidak lagi sama seperti sebelum 2020.
Fenomena ini sering digadang-gadang sebagai revolusi dunia kerja. Pekerja tidak lagi harus terjebak macet, bisa mengatur waktu lebih leluasa, bahkan bekerja lintas negara tanpa harus pindah domisili. Di sisi lain, perusahaan bisa menghemat biaya kantor, memperluas akses ke talenta global, dan menjaga produktivitas tanpa kehadiran fisik. Namun, di balik narasi indah itu, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan: jam kerja yang kabur, kesepian sosial, hingga munculnya bentuk eksploitasi baru.
Batas yang Semakin Kabur
Dulu, batas antara kerja dan rumah jelas. Begitu pulang kantor, pekerjaan selesai. Kini, notifikasi bisa masuk kapan saja. Grup WhatsApp kerja aktif 24 jam, surel menumpuk di luar jam kerja, dan budaya respons cepat jadi standar baru. Akibatnya, banyak pekerja merasa “selalu online.” Alih-alih lebih bebas, sebagian orang justru merasa lebih lelah.
Fenomena ini tidak sekadar anekdot. Survei global menemukan bahwa 54 persen pekerja merasa beban kerja mereka meningkat setelah beralih ke model remote atau hibrida. “Fleksibilitas” sering kali menjadi eufemisme bagi jam kerja yang meluas tanpa kompensasi tambahan. Dalam jangka panjang, risiko burnout dan masalah kesehatan mental meningkat.
Fleksibilitas atau Eksploitasi?
Remote work sering dipromosikan sebagai solusi win-win: pekerja lebih bahagia, perusahaan lebih hemat. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Banyak perusahaan menjadikan fleksibilitas sebagai alasan untuk melepas tanggung jawab. Biaya listrik, internet, kursi ergonomis, hingga kesehatan mata akibat layar sering kali ditanggung pekerja sendiri.
Dalam konteks global, muncul juga fenomena “offshoring baru”: perusahaan besar di negara maju merekrut pekerja dari negara berkembang dengan gaji yang jauh lebih rendah, memanfaatkan perbedaan biaya hidup. Pekerja lokal mendapat kesempatan, tetapi dalam kondisi tawar-menawar yang timpang. Fleksibilitas berubah menjadi bentuk eksploitasi yang lebih halus.
Kesenjangan Baru di Dunia Kerja
Tidak semua pekerjaan bisa dilakukan secara remote. Pekerja sektor digital, kreatif, atau jasa profesional jelas lebih diuntungkan. Mereka bisa bekerja dari rumah, kafe, bahkan pantai selama ada koneksi internet. Sementara itu, pekerja sektor informal atau berbasis lokasi—sopir, pramusaji, buruh pabrik, tenaga kesehatan—tidak punya pilihan serupa.
Kesenjangan ini menciptakan “kelas baru” di dunia kerja: mereka yang bisa bekerja dari mana saja dengan fleksibilitas tinggi, dan mereka yang tetap terikat ruang fisik dengan risiko lebih besar. Pandemi memperlihatkan betapa vitalnya tenaga kerja lapangan, tetapi justru kelompok ini yang paling sedikit mendapat perlindungan dan kesempatan fleksibilitas. Jika tren ini dibiarkan, dunia kerja bisa semakin eksklusif dan menambah ketidakadilan sosial.
Aspek Sosial yang Hilang
Selain persoalan jam kerja dan kesenjangan, ada satu hal yang kerap terlupakan: dimensi sosial. Bagi sebagian orang, kantor bukan sekadar tempat kerja, tetapi juga ruang interaksi, belajar, dan membangun jaringan.
Bekerja sepenuhnya dari rumah dapat menimbulkan rasa kesepian, terutama bagi generasi muda yang baru masuk dunia kerja. Mereka kehilangan kesempatan informal—obrolan singkat di pantry, mentoring spontan dari senior, atau bahkan sekadar nongkrong setelah jam kantor. Dalam jangka panjang, isolasi ini bisa memengaruhi perkembangan karier, kreativitas, dan kesehatan mental.
Masa Depan Kerja yang Manusiawi
Pertanyaan besarnya: bagaimana membuat fleksibilitas ini tetap manusiawi? Ada beberapa jalan yang bisa ditempuh.
Pertama, perusahaan perlu menetapkan jam kerja yang jelas, termasuk hak pekerja untuk benar-benar “offline” di luar jam kerja. Negara-negara Eropa sudah mulai mengadopsi aturan right to disconnect, yang memberi dasar hukum bagi pekerja untuk menolak pesan atau panggilan kerja setelah jam tertentu.
Kedua, perusahaan harus menanggung sebagian beban biaya remote work. Kursi ergonomis, paket kesehatan, atau subsidi internet bukan sekadar fasilitas, tetapi investasi untuk menjaga produktivitas jangka panjang.
Ketiga, pekerja juga perlu beradaptasi. Mengatur disiplin diri, membuat batas antara ruang kerja dan ruang pribadi, serta menjaga koneksi sosial di luar kantor menjadi kunci agar remote work tidak merusak keseimbangan hidup.
Terakhir, pemerintah tidak boleh tinggal diam. Regulasi ketenagakerjaan harus diperbarui agar fleksibilitas tidak menjadi alasan bagi perusahaan untuk mengurangi hak pekerja. Di Indonesia, aturan mengenai jam kerja, lembur, dan kesehatan kerja masih berorientasi pada kantor fisik. Padahal, realitas kerja sudah jauh berubah.
Menuju Jalan Tengah
Mungkin pertanyaan yang lebih realistis bukan “apakah kita akan kembali ke kantor penuh?” atau “apakah semua harus remote?” Melainkan: bagaimana menemukan jalan tengah. Model kerja hibrida, yang menggabungkan kehadiran fisik dengan fleksibilitas digital, tampaknya menjadi pilihan banyak perusahaan. Tetapi agar benar-benar adil, model ini harus dirancang dengan prinsip keseimbangan—bukan sekadar efisiensi biaya.
Penutup
Bekerja dari mana saja memang membuka peluang baru, dari karier lintas negara hingga keseimbangan hidup yang lebih baik. Tetapi ia juga membawa risiko eksploitasi yang lebih halus: jam kerja tanpa batas, biaya tersembunyi, hingga kesenjangan sosial yang melebar.
Jalan ke depan bukanlah kembali ke pola lama, melainkan merancang masa depan kerja yang seimbang: fleksibel, adil, dan tetap berpusat pada manusia. Demokrasi ekonomi seharusnya tidak berhenti di kotak suara, tetapi juga hadir dalam ruang kerja sehari-hari. Jika kita mampu menjaga fleksibilitas agar tidak berubah menjadi bentuk perbudakan baru, maka “bekerja dari mana saja” bisa benar-benar menjadi simbol kemerdekaan, bukan jebakan modernitas.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”