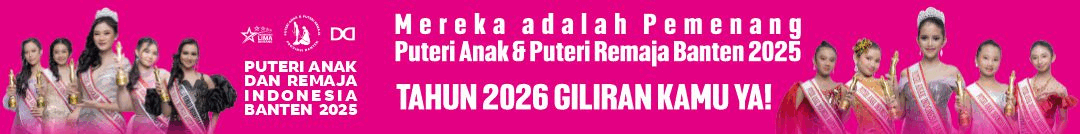Pernah nggak sih kamu sampai lupa hari dan tanggal gara-gara sibuk banget sama aktivitas? atau merasa bersalah hanya karena sehari tidak melakukan apa-apa? Rasa bersalah itu seolah-olah sudah menjadi gaya hidup zaman sekarang yang biasa dikenal dengan hustel culture. Beberapa tahun terakhir, istilah hustle culture semakin akrab terdengar di kalangan mahasiswa. Gaya hidup yang identik dengan kesibukan tanpa henti ini sering dianggap sebagai simbol produktivitas. Dari pagi sampai siang kuliah, sorenya rapat organisasi, lanjut mengerjakan tugas di malam hari, bahkan ditambah kegiatan lomba atau magang, menjadi rutinitas yang biasa ditemui. Namun di balik kesan ambisius dan keren itu, tidak sedikit mahasiswa yang akhirnya kelelahan secara fisik maupun mental.
Fenomena ini menunjukkan bahwa hustle culture memang punya sisi negatif. GoodStats mencatat bahwa hampir 72% mahasiswa Indonesia mengalami burnout akibat tekanan akademik dan aktivitas non-akademik yang terlalu padat. Bahkan, sebagian besar merasa kesehatan mentalnya terganggu karena tuntutan untuk selalu terlihat produktif. Kesibukan yang semestinya menjadi ajang belajar justru berubah menjadi beban, karena dijalani tanpa perhitungan dan jeda. Dalam konteks pengelolaan diri, kondisi ini mirip dengan beban kerja berlebihan yang jika tidak diatur, akan menurunkan motivasi sekaligus performa individu.
Media sosial menjadi salah satu faktor yang memperkuat fenomena ini. Platform digital sepeti Instagram, LinkedIn dan lainnya sering menjadi etalase pencapaian, mulai dari magang di tempat yang bergengsi, memenangkan lomba dan kompetisi, hingga sukses menjalankan kepanitiaan besar. Melihat teman-teman mengunggah prestasi mereka di media sosial menimbulkan rasa takut tertinggal atau FOMO. Yang pada akhirnya, banyak mahasiswa terdorong untuk ikut-ikutan sibuk agar tidak dianggap malas, tekanan ini membuat produktivitas terasa seperti kewajiban sosial yang tidak tertulis, serupa dengan budaya kerja yang menuntut orang selalu tampil sibuk.
Meski begitu, menilai hustle culture hanya dari sisi negatif jelas tidak adil. Faktanya, banyak mahasiswa justru memperoleh manfaat dari kesibukan yang dikelola dengan baik. Dengan mengikuti kegiatan organisasi mereka dapat melatih keterampilan komunikasi, membangun relasi, dan kepemimpinan; dengan mengikuti lomba dapat mengasah kemampuan berpikir di bawah tekanan; sementara dengan adanya kepanitiaan mengajarkan mengenai kerja sama. Semua ini merupakan soft skill yang tidak hanya berguna di masa kuliah, tetapi juga menjadi bekal menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif. Soft skill inilah yang nantinya sangat dihargai oleh perusahaan, karena menjadi pelengkap keterampilan teknis dalam membentuk individu yang siap berkontribusi.
Tantangan sebenarnya adalah bagaimana mahasiswa bisa memilah aktivitas sesuai kapasitas dan tujuan jangka panjang mereka. Tidak semua kesempatan harus diambil, karena kualitas pengalaman lebih berharga daripada sekadar kuantitas kegiatan. Dengan mengatur ritme, mahasiswa dapat menghindari risiko burnout dan tetap memperoleh manfaat dari aktivitas yang dijalani. Artinya, hustle culture bisa menjadi investasi ketika dijalani secara selektif dan seimbang. Hal ini sama seperti pentingnya merancang pekerjaan agar sesuai dengan kemampuan individu, sehingga produktivitas tetap tinggi tanpa mengorbankan kesehatan mental.
Hustle culture bukan soal siapa yang paling sibuk atau siapa yang punya CV paling panjang. Lebih dari itu, ia adalah pilihan bagaimana kita memaknai kesibukan selama kuliah. Apakah hanya sekadar ikut arus tuntutan, atau menjadikannya sarana untuk bertumbuh. Mahasiswa yang mampu mengelola ritme hidupnya akan keluar bukan hanya dengan ijazah, tapi juga dengan karakter dan keterampilan yang membuatnya siap menghadapi dunia nyata. Karena itu, daripada terjebak dalam burnout, lebih baik kita belajar menata kesibukan sebagai investasi diri. Karena di masa depan, yang dihargai bukan seberapa banyak kegiatan yang pernah diikuti, tapi seberapa matang diri kita terbentuk karenanya.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”