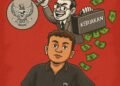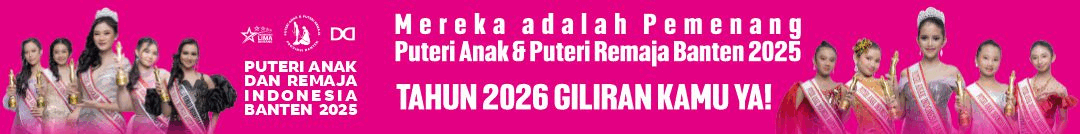Lingkungan kampus biasa didefinisikan sebagai lingkungan yang ideal untuk mahasiswa menuntut ilmu dan berkembang menjadi manusia yang lebih dewasa dan berkualitas karena disanalah “katanya” kebebasan berpikir dijunjung tinggi, keberagaman dihormati, dan rasa empati menjadi nilai dasar. Gelar MAHASISWA yang biasa diagung-agungkan karena kata maha di atas siswa yang menggambarkan keagungan peran pengabdian ilmu dalam masyarakat. Tetapi, dibalik citra intelektual tersebut terdapat banyak realitas yang sangat berkebalikan dengan apa yang selama ini digambarkan. Salah satu yang “umum” terjadi di lingkungan kampus adalah perundungan atau bullying. Perundungan atau bullying di lingkungan kampus biasanya dikemas dengan label candaan, pembentukan mental, bahkan tradisi senioritas.
Lalu mengapa hal tersebut dapat terjadi dan bahkan sudah menjadi sesuatu hal yang “umum” terjadi di lingkungan kampus? Bullying di lingkungan kampus bukan muncul begitu saja, tetapi tumbuh dari rasa kompetitif yang mendorong mahasiswa untuk selalu menjadi yang terbaik bahkan harus “tahan banting” dari segala tekanan. Lama kelamaan, hal tersebutlah yang menyebabkan terkikisnya rasa empati terhadap perasaan orang lain.
Salah satu sumber utama perundungan di lingkungan kampus lahir dari budaya senioritas. Banyak organisasi mahasiswa atau unit kegiatan mahasiswa masih menjunjung “penggemblengan” dengan alasan untuk membentuk mental dan solidaritas. Sayangnya, di balik hal tersebut sering terselip hal-hal yang tidak menggambarkan karakter yang baik misalnya intimidasi, pelecehan verbal, hingga kekerasan fisik. Senior dianggap memiliki wewenang untuk “mendidik” junior dengan cara kasar, sedangkan junior secara tidak langsung tidak berhak untuk melawan karena takut dicap tidak hormat. Hal tersebut secara tidak langsung menormalisasikan ketimpangan kekuasaan dan membentuk hierarki sosial yang berkembang tanpa kontrol.
Fenomena bullying di kalangan mahasiswa dapat memberikan efek jangka panjang bagi korbannya salah satunya yaitu menciptakan rasa tidak aman dan terisolasi. Lebih lanjut lagi, banyak korban yang memilih diam karena doktrin yang diberikan bahwa “penggemblengan” yang ada memang diperlukan untuk pembentukan mental sehingga korban takut akan disalahkan dan dianggap lemah. Hal tersebut menciptakan keterbatasan interaksi sosial yang sehat, menyebabkan kecemasan, menurunkan tingkat kepercayaan diri, bahkan menyebabkan stress dan depresi. Namun tragisnya, akibat dari tekanan dan luka yang ditimbulkan dari tindakan bullying, tak jarang para korban lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya. Hal tersebut menunjukkan adanya kegagalan sistem yang membuat korban merasa tidak aman untuk berbicara dan bahkan lingkungan yang tutup mata karena merasa hal tersebut bukanlah tanggung jawabnya atau biasa disebut sebagai bystander effect. Pada akhirnya, korban merasa tidak lagi punya tempat yang aman dimana ia dapat diterima apa adanya sehingga ketika rasa terasing dan ketidakberdayaan memuncak, sebagian korban melihat kematian sebagai satu-satunya jalan keluar dari penderitaan yang tak terlihat. Hal teresebut seharusnya menjadi alarm peringatan bagi pihak kampus bahwa tindakan bullying harus ditangani dengan tegas karena ia dapat “membunuh” secara perlahan, baik secara mental maupun fisik. Setiap kali terdapat berita mengenai mahasiswa yang bunuh diri karena bullying selalu muncul pertanyaan “kok bisa?” atau “kenapa engga cerita?”. Padahal pertanyaan yang paling utama adalah “apakah lingkungan kampusnya tidak lagi terasa nyaman untuk mereka bercerita?”
Setelah tragedi terjadi, tak jarang kita sibuk untuk mencari kambing hitam untuk disalahkan atas apa yang terjadi. Tapi sebenenarnya, bullying di kampus merupakan hasil dari sistem yang membiarkan kekerasan berjalan tanpa konsekuensi. Fenomena tersebut sudah seharusnya menjadi refleksi bagi seluruh civitas akademika untuk meninjau kembali nilai-nilai yang selama ini dijunjung di lingkungan kampus. Bukan malah menyapu kasus perundungan di bawah karpet demi menjaga citra baik kampus. Budaya “pembentukan mental” yang biasa menjadi alasan tragedi perpeloncoan perlu dikaji ulang agar tidak melanggengkan tradisi senioritas. Pembentukan karakter seharusnya dilakukan dengan metode-metode yang edukatif, empatik, dan menunjukkan kesetaraan, bukan lewat intimidasi, penghinaan, atau tekanan psikologis.
Kampus seharusnya menjadi tempat yang aman di mana setiap langkah memiliki arti, setiap suara di dengar, dan setiap perbedaan dihargai. Dengan menciptakan ruang aman bagi mahasiswa, kampus tak hanya akan melahirkan orang yang berintelektual, tapi juga orang yang matang secara emosional. Lingkungan akademik yang sehat, tak hanya dilihat dari prestasi intelektual semata, tapi juga sejauh mana lingkungan kampus dapat membentuk rasa kemanusiaan dan rasa empati bagi mahasiswanya. Ketika ruang belajar tidak menjadi ruang yang aman, maka makna dari kata “mahasiswa” perlahan akan terkikis. Sebab, bagaimana seseorang bisa memahami dunia luar jika di lingkungannya sendiri ia tidak merasa aman?
Namun, alih-alih mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi dalang yang harus bertanggung jawab atas tragedi yang ada, kita juga harus mengambil langkah yang tak kalah penting untuk membangun kesadaran dan komitmen bersama agar tragedi serupa tidak kembali terulang. Pada akhirnya, yang menjadi hal utama adalah bagaimana kita semua bergerak bersama untuk memastikan tidak lagi ada nyawa yang hilang karena penderitaan yang mereka alami. Kampus, mahasiswa, dan negara harus berjalan di arah yang sama untuk membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif. Karena suatu perubahan tidak dapat datang dari satu pihak saja, maka diperlukan keberanian bersama untuk mengakui kesalahan, memperbaiki sistem, dan menciptakan ruang belajar yang benar-benar manusiawi.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”