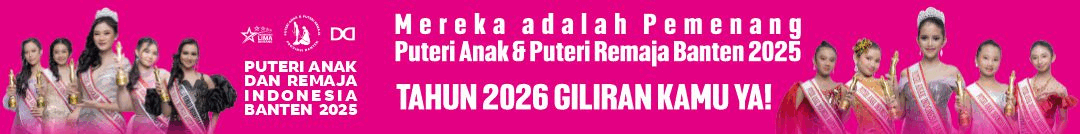Laporan Transparency International tahun 2024 menempatkan Indonesia pada skor 37 dari 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI), dengan peringkat 99 dari 180 negara. Meski naik tiga poin dari tahun sebelumnya, angka ini tetap menunjukkan bahwa korupsi masih mengakar kuat dan publik menilai lembaga-lembaga negara belum sepenuhnya dapat dipercaya. Dalam konteks inilah, pembahasan tentang kepercayaan kelembagaan menjadi mendesak—sebab menurunnya indeks korupsi bukan hanya cermin dari lemahnya hukum, tetapi juga tanda erosi legitimasi negara.
Korupsi selalu jadi wajah paling telanjang dari krisis kepercayaan. Ia tidak hanya mencuri uang rakyat, tetapi juga mencuri keyakinan apakah negara masih bekerja untuk kepentingan publik. Di Indonesia, persoalan ini bukan lagi sekadar perilaku individu, melainkan gejala dari lembaga-lembaga yang kehilangan arah moral dan fungsi pengawasan. Krisis kepercayaan kelembagaan kini menjalar dari parlemen, lembaga penegak hukum, hingga badan usaha milik negara (BUMN). Di tengah semua itu, Pertamina menjadi contoh paling gamblang—sebuah institusi strategis yang berubah dari simbol kedaulatan energi menjadi simbol rapuhnya integritas negara.
Korupsi dan Runtuhnya Legitimasi
Francis Fukuyama (1995) menyebut kepercayaan sebagai modal sosial—pondasi tak kasat mata yang memungkinkan lembaga publik berfungsi tanpa pengawasan berlebihan. Begitu kepercayaan itu hilang, biaya sosial melonjak: pengawasan harus diperketat, kebijakan menjadi defensif, dan publik berhenti percaya pada janji perubahan.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, United Nations Development Programme (UNDP, 1997) menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan prasyarat utama good governance—suatu tata kelola yang berlandaskan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi. Jika prinsip-prinsip itu melemah, maka ruang korupsi melebar dan legitimasi negara menyusut.
Di Indonesia, rantai peristiwa korupsi dalam lembaga-lembaga negara telah menumpuk, menciptakan keletihan sosial yang dalam. Kasus korupsi di tubuh Pertamina, dengan estimasi kerugian Rp285 triliun dalam tata kelola minyak dan produk kilang periode 2018–2023, memperkuat keyakinan bahwa sistem pengawasan hanya kuat di atas kertas. Ketika mantan Direktur Utama Pertamina dijatuhi hukuman 13 tahun penjara dalam perkara LNG, publik tidak lagi bertanya “siapa yang salah”, melainkan “siapa yang tersisa untuk dipercaya”.
Dalam kerangka teori principal–agent (Jensen & Meckling, 1976), korupsi seperti ini dapat dibaca sebagai bentuk kegagalan hubungan antara rakyat sebagai principal dan lembaga negara sebagai agent. Ketika pengawasan lemah dan insentif tidak seimbang, agen publik cenderung menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Di titik inilah kepercayaan kelembagaan berubah dari modal sosial menjadi beban sosial —karena publik harus menanggung biaya dari ketidakjujuran birokrasi yang seharusnya melayani mereka.
Krisis kepercayaan ini tidak berdiri sendiri. Ia tumbuh dari pola yang sama: keputusan diambil dalam ruang tertutup, pengawasan internal tidak independen, dan komunikasi publik lebih sibuk meredam citra daripada menjelaskan fakta. Pertamina hanya satu dari banyak lembaga yang menunjukkan bagaimana korupsi menggerus fondasi kepercayaan kelembagaan yang dulu menopang legitimasi negara.
Jejaring yang Gagal Diawasi
Mark Granovetter (1985) menulis bahwa keputusan ekonomi selalu tertanam (embedded) dalam jaringan sosial antar-aktor—dari manajemen hingga pengawas. Dalam jejaring yang terlalu rapat, solidaritas berubah menjadi kolusi, dan koreksi dari luar berhenti bekerja. Pertamina memperlihatkan pola itu dengan jelas: dari tata kelola minyak yang bermasalah hingga isu pencampuran bahan bakar yang mengaburkan mutu dan transparansi kebijakan energi.
Bagi publik, perdebatan istilah “blending” atau “oplosan” tidak lagi relevan. Yang penting bukan kadar oktan, tapi kadar kejujuran. Ketika pengawasan mutu dipertanyakan dan penjelasan teknis berubah-ubah, masyarakat membaca satu pesan: lembaga sebesar Pertamina pun bisa kehilangan integritas dasar. Di situ, korupsi tak lagi sekadar kejahatan finansial, tapi tanda dari runtuhnya etika kelembagaan.
Dalam perspektif Robert D. Putnam (1993), kepercayaan publik adalah bagian dari social capital yang memperkuat ikatan antara negara dan warga. Ketika lembaga publik gagal menjaga kredibilitas, modal sosial itu ikut menurun. Akibatnya, masyarakat lebih percaya pada jejaring non-formal—pasar, komunitas, atau media sosial—daripada pada institusi resmi. Hilangnya kepercayaan ini mengubah relasi antara warga dan negara menjadi relasi transaksional semata.
Pasar yang Terkunci, Rakyat yang Tak Percaya
Karl Polanyi (1944) mengingatkan bahwa pasar tidak pernah berdiri sendiri; ia selalu melekat pada kekuasaan dan nilai yang membentuknya. Di sektor energi Indonesia, kekuasaan itu masih terkonsentrasi di tangan negara. Meski jaringan SPBU swasta seperti Shell, bp-AKR, dan Vivo terus berkembang, kebijakan impor BBM masih terkunci dalam skema satu pintu dengan Pertamina sebagai pengendali utama.
Paradoksnya, publik beralih ke swasta untuk mencari kepastian, tapi sistem pasok tetap bergantung pada lembaga yang sama. Ini bukan hanya semata persoalan monopoli ekonomi, melainkan bentuk institusional lock-in—sebuah keadaan ketika struktur ekonomi terkunci pada satu lembaga pengendali. Dalam sistem yang demikian, publik berada di posisi paling rentan—mereka harus bergantung pada mekanisme yang tidak sepenuhnya transparan, namun tidak memiliki daya tawar untuk menuntut perbaikan.
Kondisi ini memperlihatkan bagaimana korupsi dan kebijakan tertutup menciptakan krisis berlapis: pasar kehilangan dinamika, lembaga kehilangan legitimasi, dan publik kehilangan rasa memiliki terhadap negara. Akibatnya, hubungan antara warga dan lembaga berubah dari partisipatif menjadi pragmatis: orang membeli dari siapa yang paling dipercaya, bukan dari siapa yang mewakili negara.
Krisis Kepercayaan yang Menular
Krisis yang dialami Pertamina tidak berhenti di sektor energi. Ia mencerminkan penyakit yang kelembagaan yang menjalar ke banyak ruang negara—dari birokrasi publik hingga lembaga penegak hukum. Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri menghadapi krisis integritas, publik semakin kehilangan jangkar moral untuk percaya pada institusi mana pun. Dalam situasi seperti ini, setiap tindakan pemerintah—betapapun baik niatnya—mudah dicurigai sebagai bagian dari permainan kuasa.
Krisis kepercayaan kelembagaan akhirnya menjadi krisis negara. Ia menggerus legitimasi politik, memperlemah efektivitas kebijakan, dan menurunkan kualitas demokrasi. Dalam logika Fukuyama dan Putnam, masyarakat yang kehilangan kepercayaan akan membangun sistemnya sendiri di luar negara—dari pasar informal hingga opini publik digital—karena negara tidak lagi dianggap pelindung, melainkan sebagai ancaman terhadap kesejahteraan dan kebenaran.
Menutup Retakan: Jalan Pemulihan Kepercayaan
Krisis kepercayaan publik yang berulang menandakan persoalan struktural di dalam lembaga negara. Masalahnya bukan hanya pada pelanggaran hukum, tetapi pada sistem kerja yang tidak memberi ruang koreksi dan pertanggungjawaban. Selama lembaga publik beroperasi tanpa mekanisme pengawasan yang efektif dan keterbukaan yang nyata, kepercayaan akan terus menurun, apa pun bentuk kebijakannya.
Reformasi kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak untuk memperbaiki fondasi itu. Perubahan harus dimulai dari hal-hal yang paling dasar—kejelasan tanggung jawab, proses yang bisa diaudit, dan data yang terbuka untuk publik. Pertamina menjadi contoh nyata betapa lemahnya tata kelola bisa menciptakan dampak sistemik, bukan hanya pada ekonomi, tapi juga pada persepsi publik terhadap integritas negara. Reformasi harus diarahkan untuk membangun sistem yang mampu bekerja secara transparan dan mengoreksi dirinya sendiri, tanpa menunggu tekanan dari luar.
Reformasi kelembagaan adalah syarat agar negara kembali dipercaya. Keberhasilan membangun kepercayaan tidak ditentukan oleh pidato politik, tetapi oleh lembaga yang berfungsi dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika perubahan ini dijalankan secara konsisten, Indonesia Emas 2045 tidak akan berhenti sebagai slogan pembangunan, tetapi menjadi bukti bahwa negara telah belajar memperbaiki dirinya dan kembali layak dipercaya rakyatnya.
Referensi
Fukuyama, F. (1995). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York, NY: Free Press.
Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. American Journal of Sociology, 91(3), 481–510.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.
Polanyi, K. (1944). The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Boston, MA: Beacon Press.
Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Tempo. (2025, Februari 26). Kejagung Jelaskan Praktik Blending BBM RON 90 Jadi 92 di Pertamina Periode 2018-2023. Tempo.co. https://news.republika.co.id/berita/ssaah0409/kejagung-jelaskan-praktik-blending-bbm-ron-90-jadi-92-di-pertamina-periode-20182023
Liputan6.com. (2025, September 10). Kementerian ESDM Minta Shell dan BP AKR Serahkan Data BBM, Pertamina Siap Pasok. Liputan6.com. https://www.liputan6.com/bisnis/read/6156099/kementerian-esdm-minta-shell-dan-bp-akr-serahkan-data-bbm-pertamina-siap-pasok
Detik.com. (2025). Hukuman Karen Agustiawan Diperberat MA Jadi 13 Tahun Penjara. Detik.com. https://news.detik.com/berita/d-7799678/hukuman-karen-agustiawan-diperberat-ma-jadi-13-tahun-penjara
Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index 2024: Indonesia. Transparency International. https://www.transparency.org/en/cpi/2024/index/idn
United Nations Development Programme (UNDP). (1997). Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document. New York, NY: United Nations Development Programme.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”