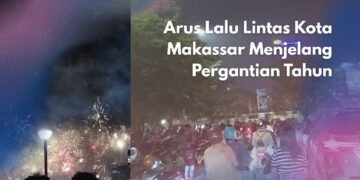Pada tanggal 27 Juli 2025, publik Indonesia kembali disodorkan kenyataan pahit: perusakan rumah doa di Padang, Sumatera Barat. Peristiwa ini bukan sekadar berita lokal yang akan tenggelam dalam pusaran hiruk-pikuk nasional dan global, melainkan manifestasi nyata dari erosi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan yang selama ini diagung-agungkan. Ketika intoleransi merebak di jantung negeri sendiri, dan negara memilih diam atau bahkan abai, kita sedang menyaksikan degradasi serius terhadap identitas bangsa.
Indonesia telah lama membanggakan diri sebagai bangsa plural, berlandaskan Pancasila dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan sebaliknya. Peristiwa di Padang hanya satu dari serangkaian insiden intoleransi yang telah berulang kali terjadi—tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi juga di berbagai penjuru negeri. Kita masih ingat betul rekam jejak kelam yang terus berulang: penolakan pembangunan gereja di Dharmasraya (2012) dan Sijunjung (2013), pemaksaan penggunaan jilbab kepada siswi non-Muslim di SMK Negeri Padang (2020), hingga pembubaran ibadah, intimidasi, dan perusakan rumah ibadah di Cilegon (2021), Bangka Belitung (2023), bahkan Bogor (2024). Kejadian-kejadian ini membentuk pola yang mencerminkan toleransi yang semakin lapuk dan negara yang gagal menjalankan peran konstitusionalnya sebagai pelindung seluruh rakyat, tanpa kecuali.
Serangkaian insiden telah mengguncang pondasi toleransi di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat, menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Pada 21 Januari 2012, di Dharmasraya, Sumatera Barat, terjadi penolakan pembangunan gereja HKBP dan HKI. Tak lama berselang, Februari 2013, Sijunjung, Sumatera Barat, menjadi saksi penolakan serupa terhadap pembangunan gereja dan aktivitas keagamaan jemaat Protestan. Puncaknya pada 21 Juli 2018, di Nagari Sungai Dareh, Dharmasraya, Sumatera Barat, sebuah bangunan gereja HKBP bahkan dibongkar paksa oleh massa.
Isu intoleransi juga merambah institusi pendidikan, seperti yang terjadi pada 24 Januari 2020 di Padang, Sumatera Barat, ketika muncul kontroversi dan dugaan pemaksaan penggunaan jilbab bagi siswi non-Muslim di SMK Negeri 2 Padang. Pola penolakan pembangunan dan gangguan ibadah terus berlanjut di berbagai daerah. Pada 17 Maret 2021, Cilegon, Banten, menghadapi penolakan dan intimidasi terhadap pembangunan gereja di Kecamatan Grogol. Kekerasan bahkan terjadi pada 25 Desember 2021 di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dengan penyerangan dan perusakan gereja Katolik St. Mikael oleh sekelompok massa.
Pembubaran ibadah menjadi pemandangan yang menyedihkan, seperti yang dialami umat Kristen di perumahan Serang, Banten, pada 19 Maret 2022, dan pembubaran ibadah Natal di Gereja Kristen Kemah Daud, Bandar Lampung, pada 11 Desember 2022. Kemudian, pada 12 April 2023, Bangka Belitung menyaksikan penolakan dan intimidasi terhadap pembangunan gereja di Desa Tanjung Gunung. Terbaru, 8 Mei 2024, di Parung, Bogor, Jawa Barat, ibadah jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin turut dibubarkan. Kejadian-kejadian ini bukan sekadar insiden terpisah, melainkan cerminan dari tantangan serius terhadap nilai-nilai toleransi dan keberagaman di Indonesia.
Ada ironi menyakitkan ketika perhatian pejabat publik dan narasi media nasional lebih sibuk pada konflik di luar negeri Palestina, Ukraina, Sudan sementara luka-luka dalam negeri dibiarkan bernanah. Bukan berarti kita tidak perlu peduli pada konflik global, tetapi menjadi sangat bermasalah ketika kepedulian itu tidak disertai dengan kepekaan terhadap tragedi kemanusiaan di rumah sendiri. Sebagian pihak mungkin berdalih bahwa insiden-insiden ini adalah urusan lokal, atau hanya ulah sekelompok kecil yang tidak mewakili masyarakat luas. Namun, ketika negara tidak hadir untuk meluruskan, menindak tegas pelaku, dan melindungi korban, maka keheningan itu menjadi bentuk pembiaran bahkan, bentuk kekerasan struktural yang lebih halus tapi mematikan.
Yang paling merasakan dampaknya tentu bukan para elite, melainkan warga biasa: jemaat yang tak bisa beribadah, anak-anak yang tumbuh dalam ketakutan, serta komunitas yang dicurigai hanya karena perbedaan iman. Mereka kehilangan ruang aman, kehilangan rasa memiliki terhadap negeri ini. Trauma sosial yang ditinggalkan tidak hanya menghancurkan rasa percaya terhadap negara, tetapi juga merusak benih-benih toleransi antarwarga.
Apa yang akan diwarisi oleh generasi muda jika mereka terus-menerus menjadi saksi (atau korban) ketidakadilan ini? Mereka belajar bahwa menjadi minoritas berarti siap dipinggirkan. Bahwa perbedaan berarti ancaman. Bahwa hukum tidak hadir untuk semua. Ini adalah investasi sosial yang amat berbahaya, karena memupuk intoleransi laten yang suatu hari bisa meledak lebih besar.
Konstitusi jelas: negara wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka, ketika minoritas harus berjuang untuk sekadar hidup damai dan beribadah, kita seharusnya marah—bukan hanya sebagai sesama warga negara, tetapi sebagai manusia. Tugas negara bukan hanya membentuk peraturan, tetapi memastikan penegakannya secara adil dan tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat tidak bisa berlindung di balik otonomi daerah untuk melepaskan tanggung jawab. Aparat keamanan tidak boleh ragu bertindak hanya karena takut dianggap “melawan arus mayoritas”. Dan pendidikan tidak boleh terus dibiarkan menjadi ruang subur bagi pengajaran kebencian yang dibalut moralitas sempit.
Sudah cukup kita tenggelam dalam retorika toleransi. Yang dibutuhkan sekarang adalah: penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku intoleransi, termasuk aktor intelektual di baliknya; evaluasi kebijakan daerah dan praktik pendidikan yang mengandung unsur diskriminatif terhadap kelompok minoritas; peningkatan literasi keberagaman melalui kurikulum yang inklusif, pelatihan guru, dan media sosial yang bertanggung jawab; serta dialog antarumat berkelanjutan yang difasilitasi oleh negara dan masyarakat sipil sebagai ruang membangun empati dan meruntuhkan prasangka.
Jika negara terus membiarkan intoleransi tumbuh tanpa perlawanan, maka kita sedang menggali lubang bagi perpecahan bangsa sendiri. Bila suara hati dari Ranah Minang dan dari pelosok lainnya tak lagi didengar, maka jeritan berikutnya bisa lebih nyaring atau lebih senyap tapi sama-sama menyakitkan. Tragedi di Padang adalah cermin retak dari wajah Indonesia hari ini. Kita bisa memilih untuk menambalnya dengan keadilan, keberanian, dan ketegasan atau membiarkannya pecah berkeping-keping. Negara, jangan hanya hadir sebagai slogan. Hadirlah sebagai pelindung nyata bagi semua, termasuk mereka yang berbeda. Karena jika tidak, sejarah akan mencatat bukan hanya siapa yang menindas, tapi juga siapa yang memilih bungkam.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”