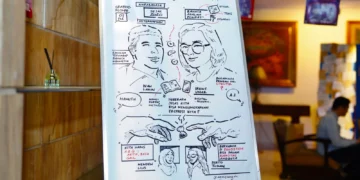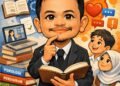Media sosial saat ini telah menjadi elemen tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Setiap harinya, jutaan masyarakat memanfaatkan platform digital seperti X (Twitter), TikTok, dan Instagram untuk berinteraksi, mengungkapkan pendapat, dan mencari informasi. Namun, di balik semua kebebasan ini, terdapat masalah serius yang mengancam kehidupan kebangsaan, yakni meningkatnya ujaran kebencian di dunia maya. Ujaran kebencian adalah bentuk interaksi yang bertujuan untuk merendahkan, menyudutkan, atau memprovokasi individu atau kelompok berdasarkan etnis, kepercayaan, ras, atau pandangan politik tertentu. Masalah ini sekarang menjadi ancaman nyata terhadap persatuan dan identitas bangsa Indonesia.
Berdasarkan kajian dari Universitas Gadjah Mada (UGM), lonjakan ujaran kebencian di dunia digital terjadi dengan cepat karena faktor psikologis dan teknologi. Banyak pengguna media sosial merasa bebas berbicara tanpa batas berkat anonimitas atau penggunaan identitas palsu. Hal ini mendorong beberapa orang untuk mengucapkan kata-kata kasar, penghinaan, bahkan fitnah tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Situasi ini semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat literasi digital masyarakat serta algoritma media sosial yang justru menonjolkan konten provokatif karena dianggap menarik bagi pengguna lainnya.
Data dari Polri yang diperoleh dari laporan Pusat Informasi Kriminal Nasional juga menunjukkan adanya peningkatan laporan terkait ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Misalnya, pada tahun 2021, tercatat 118 laporan mengenai ujaran kebencian online, yang meningkat menjadi 162 laporan pada tahun 2022. Sedangkan untuk kasus pencemaran nama baik, jumlah laporan bertambah dari 1.258 kasus pada 2018 menjadi 1.794 kasus pada 2020. Kenaikan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sering menjadi target ujaran kebencian, atau setidaknya semakin sering melaporkannya.
Dampak dari penyebaran ujaran kebencian ini sangat serius. Ketika narasi yang penuh kebencian terus disebarluaskan, ia akan menghasilkan prasangka serta kebencian di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Hal ini membuat masyarakat mudah terpecah, kehilangan rasa saling percaya, dan menurunkan semangat gotong royong yang selama ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengikis rasa nasionalisme dan melemahkan dan identitas kebangsaan kita sebagai warga negara yang mengedepankan nilai persatuan dalam keberagaman.
Menghadapi tantangan ini memerlukan kesadaran bersama dari berbagai pihak. Pemerintah telah berusaha menegakkan hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta mengawasi konten yang bermuatan kebencian. Namun, tindakan hukum saja tidak cukup tanpa dukungan dari masyarakat. Setiap warga negara harus meningkatkan literasi digital mereka untuk dapat membedakan antara kritik yang membangun dan ujaran kebencian yang merugikan. Sekolah dan lembaga pendidikan juga berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, serta tanggung jawab saat menggunakan media digital.
Di sisi lain, platform media sosial perlu memperkuat sistem moderasi konten agar unggahan yang mengandung kebencian dapat segera dibatasi. Selain itu, masyarakat sipil dapat mendorong lahirnya gerakan positif di ranah maya seperti kampanye “Saring Sebelum Sharing” atau “Klik untuk Kebaikan” untuk menciptakan budaya komunikasi yang sehat. Langkah ini sejalan dengan semangat Pancasila yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan persatuan sebagai fondasi kehidupan berbangsa.
Fenomena ujaran kebencian di dunia digital sejatinya bukan hanya isu etika berbahasa, melainkan juga gambaran dari krisis identitas kebangsaan. Jika masyarakat terus terbiasa dengan narasi yang memecah belah, maka semangat persaudaraan dan rasa cinta terhadap tanah air akan semakin memudar. Oleh karena itu, menjaga ruang digital agar tetap damai dan beradab adalah tanggung jawab bersama. Sehingga dengan literasi, kesadaran, dan empati, kita bisa menjadikan media sosial sebagai sarana memperkuat, bukan merusak, identitas bangsa Indonesia.
Oleh Afni Aulia Rahma
Artikel ini ditulis untuk memenuhi tugas Ujian Tengah Semester (UTS)
Mata Kuliah Kewarganegraan
Dosen Pengampu, Bapak Dr Ujang Jamaludin, S.Pd., M.Si., M.Pd.
Sumber:
Kementerian Komunikasi dan Informatika (2024), Laporan Tahunan Literasi Digital Nasional
Universitas Gadjah Mada (2023), “Kenapa Hate Speech Begitu Marak Terjadi di Internet”
Friedrich Naumann Foundation (2024), “Tantangan Kebebasan Berpendapat di Era Digital: Hoaks dan Ujaran Kebencian”
Bisnis.com. (2021, Maret 10). Pelaporan UU ITE Cenderung Meningkat Sejak 2018-2020. Diakses dari https://kabar24.bisnis.com/read/20210310/16/1366254/polri-pelaporan-uu-ite-cenderung-meningkat-sejak-2018-2020
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”