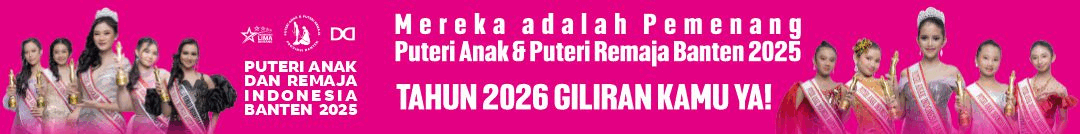Menjaga Akar Ekosistem Pesisir: Menyelami Manfaat Mangrove di Sulawesi Utara
Manado, Hamparan hutan mangrove yang membentang dari pesisir Molas hingga Wori di Sulawesi Utara bukan hanya lanskap hijau yang meneduhkan mata. Lebih dari itu, kawasan ini merupakan ekosistem kompleks yang menyimpan potensi ilmiah, ekonomi, dan sosial yang signifikan. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa mangrove bukan sekadar tanaman pesisir, melainkan salah satu solusi paling efektif untuk berbagai persoalan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Secara ekologis, mangrove dikenal sebagai bagian dari “ekosistem karbon biru”, suatu istilah yang merujuk pada kemampuan luar biasa vegetasi pesisir dalam menyerap dan menyimpan karbon. Studi Donato dan timnya (2011) mencatat bahwa hutan mangrove mampu menyimpan karbon hingga tiga kali lipat lebih banyak per hektare dibandingkan hutan tropis daratan. Temuan serupa juga dijumpai di kawasan Bahowo, Kelurahan Tongkaina, Kota Manado, yang menunjukkan tingginya kandungan karbon dalam biomassa mangrove lokal.
Lebih jauh, akar mangrove yang menjalar kuat di tanah berlumpur memiliki fungsi protektif terhadap abrasi dan erosi pantai. Struktur akar ini juga terbukti mampu meredam kekuatan gelombang laut, bahkan mengurangi dampak bencana tsunami. Penelitian di berbagai wilayah rawan abrasi, termasuk di pesisir Jakarta, memperlihatkan efektivitas mangrove sebagai benteng alami yang tak tergantikan.
Tidak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah penting bagi berbagai biota laut. Struktur akar yang rapat dan terlindung menyediakan tempat pemijahan dan pengasuhan (nursery ground) bagi ikan, udang, kepiting, dan berbagai jenis moluska. Temuan dari Kabupaten Tana Tidung memperkuat fakta bahwa keberadaan mangrove mendukung kelangsungan hidup sumber daya perikanan secara berkelanjutan.
Dari sisi ekonomi, berbagai studi valuasi mangrove di Indonesia memperlihatkan manfaat langsung yang mencakup hasil tangkapan ikan, udang, kepiting, hingga kayu bakau. Namun manfaat tidak langsung seperti perlindungan garis pantai, pencegah intrusi air laut, dan penyediaan pakan alami, memiliki nilai ekonomi yang bahkan lebih besar. Studi di Desa Tongke-Tongke dan Kabupaten Barru di Sulawesi Selatan misalnya, menegaskan bahwa menjaga ekosistem mangrove jauh lebih menguntungkan secara ekonomi dibandingkan mengalihfungsikannya menjadi tambak atau lahan komersial lainnya.
Sementara dari dimensi sosial, keberadaan hutan mangrove terbukti menopang mata pencaharian masyarakat pesisir. Penelitian di Makassar menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil hutan mangrove seperti nener, udang, dan kepiting, menyumbang secara signifikan pada pendapatan rumah tangga nelayan. Di saat yang sama, potensi ekowisata mangrove mulai dilirik sebagai alternatif ekonomi baru yang berpihak pada konservasi.
Di Sulawesi Utara, pendekatan konservasi berbasis ilmiah mulai diterapkan secara lebih sistematis. Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (POKJA PMD) menjadi contoh bagaimana sains dan partisipasi masyarakat berpadu dalam mengelola ekosistem mangrove secara berkelanjutan. POKJA PMD tak hanya melakukan penanaman ulang, tetapi juga aktif dalam edukasi publik berbasis data untuk mendorong kesadaran kolektif dalam menjaga hutan mangrove.
Upaya ini menggambarkan bahwa menjaga mangrove bukan hanya urusan ekologis semata, melainkan investasi jangka panjang bagi ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Mangrove bukan sekadar deretan pohon di tepi laut, melainkan akar dari masa depan yang lebih lestari.