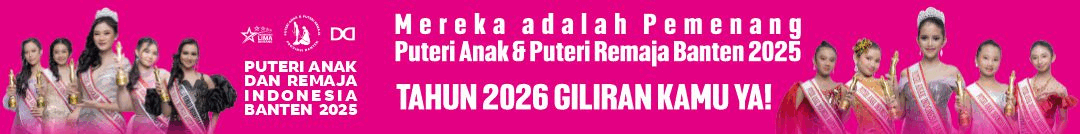Di tengah krisis energi global dan perubahan iklim yang makin nyata, Indonesia membutuhkan solusi nyata yang murah, mudah, dan berkelanjutan. Salah satu teknologi yang layak diangkat dari pinggir ke pusat perhatian adalah biodigester. Teknologi ini mampu mengubah limbah organik menjadi biogas yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif, sekaligus menghasilkan pupuk organik cair yang berguna bagi pertanian. Sederhana, bukan berarti remeh. Biodigester adalah teknologi masa depan yang sudah hadir hari ini.
Masalah energi dan limbah bukan hanya urusan kota-kota besar. Di pedesaan, terutama di daerah agraris, potensi sumber energi terbarukan justru melimpah dalam bentuk kotoran ternak, limbah dapur, dan sisa tanaman. Sayangnya, karena keterbatasan informasi dan dukungan kebijakan, limbah tersebut lebih sering dianggap masalah ketimbang peluang. Padahal, biodigester menjawab dua persoalan sekaligus: mengelola limbah dan menghasilkan energi.
Kearifan Lokal dan Teknologi Tepat Guna
Biodigester bukan teknologi canggih dari luar negeri yang sulit dipahami masyarakat desa. Justru, ia lahir dari semangat teknologi tepat guna: menyesuaikan dengan kondisi lokal, menggunakan bahan yang tersedia, dan bisa dirawat oleh masyarakat sendiri. Di beberapa desa di Jawa Tengah dan Bali, misalnya, masyarakat sudah menggunakan biodigester untuk memasak sehari-hari. Biogas yang dihasilkan dari kotoran sapi cukup untuk menggantikan kebutuhan LPG dalam skala rumah tangga.
Kisah sukses itu mestinya diperluas, bukan dibiarkan tersebar secara sporadis. Pemerintah daerah dan lembaga pendamping masyarakat harus melihat biodigester sebagai alat pemberdayaan, bukan sekadar proyek teknologi. Pembangunan biodigester bisa menjadi gerakan transformatif, memadukan pendidikan lingkungan, ketahanan energi, dan ekonomi sirkular di tingkat akar rumput.
Tantangan: Sosial, Bukan Teknologi
Salah satu kendala utama pengembangan biodigester bukanlah teknis, melainkan sosial dan perilaku. Masih ada anggapan bahwa menggunakan biogas dari kotoran ternak itu “jorok” atau “tidak layak”. Di sinilah pentingnya pendekatan edukatif yang menghormati budaya lokal. Penyuluhan, contoh nyata, dan keterlibatan tokoh masyarakat sangat menentukan keberhasilan adopsi teknologi ini.
Lebih jauh, pendanaan juga menjadi isu penting. Meskipun secara jangka panjang biodigester sangat hemat, biaya awal pembangunan unit biodigester skala rumah tangga bisa mencapai 3–6 juta rupiah. Perlu ada insentif atau skema bantuan bergulir agar masyarakat terdorong mencobanya. Di sinilah peran pemerintah dan lembaga donor sangat krusial.
Momentum Transisi Energi
Pemerintah Indonesia telah mencanangkan target transisi energi terbarukan sebesar 23% pada 2025 dan 31% pada 2050 yang masuk dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Peraturan Presiden No.98 Tahun 2021 Tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Biodigester dapat dimasukkan dalam proyek-proyek offset karbon atau perdagangan karbon (carbon trading) hal ini berpotensi menghasilkan nilai jual sertifikat karbon (carbon credit) jika diukur secara akurat. Hal ini sejalan dengan Permen LHK No. 21 Tahun 2018 Tentang baku mutu emisi gas rumah kaca, relevan untuk perhitungan emisi dari biogas (CH4, CO2). Biodigester dapat diklaim sebagai alat pengurangan emisi karbon. Sayangnya, narasi energi bersih masih didominasi oleh panel surya dan turbin angin. Biodigester seharusnya diberi ruang yang lebih besar dalam peta jalan energi nasional, karena sifatnya yang terdesentralisasi dan berbasis komunitas. Ini sejalan dengan semangat keadilan energi: bukan hanya soal mengganti sumber energi, tapi juga soal siapa yang mengakses dan mengendalikannya.
Dalam konteks krisis iklim dan subsidi energi fosil yang makin membebani APBN, biodigester memberikan alternatif cerdas yang bisa menyeimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ia bukan sekadar alat, tapi pintu masuk menuju perubahan pola pikir: dari konsumsi ke produksi, dari ketergantungan ke kemandirian.
Berdampak Besar
Biodigester adalah teknologi kecil dengan dampak besar. Ia mungkin tidak sepopuler kendaraan listrik atau PLTS, tapi potensinya di desa-desa Indonesia sangat menjanjikan. Saatnya mendorong kebijakan yang pro terhadap inisiatif energi lokal. Karena energi bukan hanya urusan negara dan kota besar. Dari perut desa, harapan energi masa depan bisa lahir—bersih, murah, dan berkelanjutan.