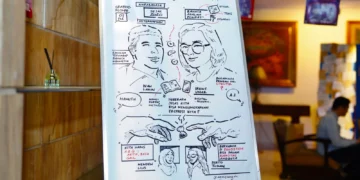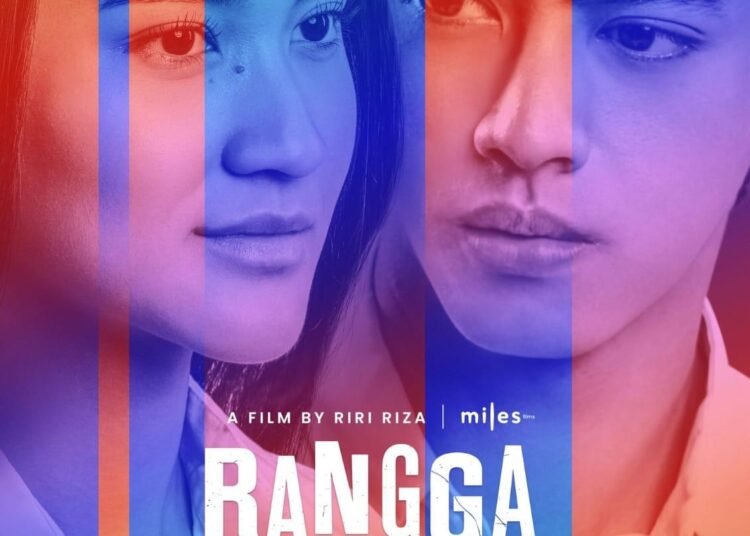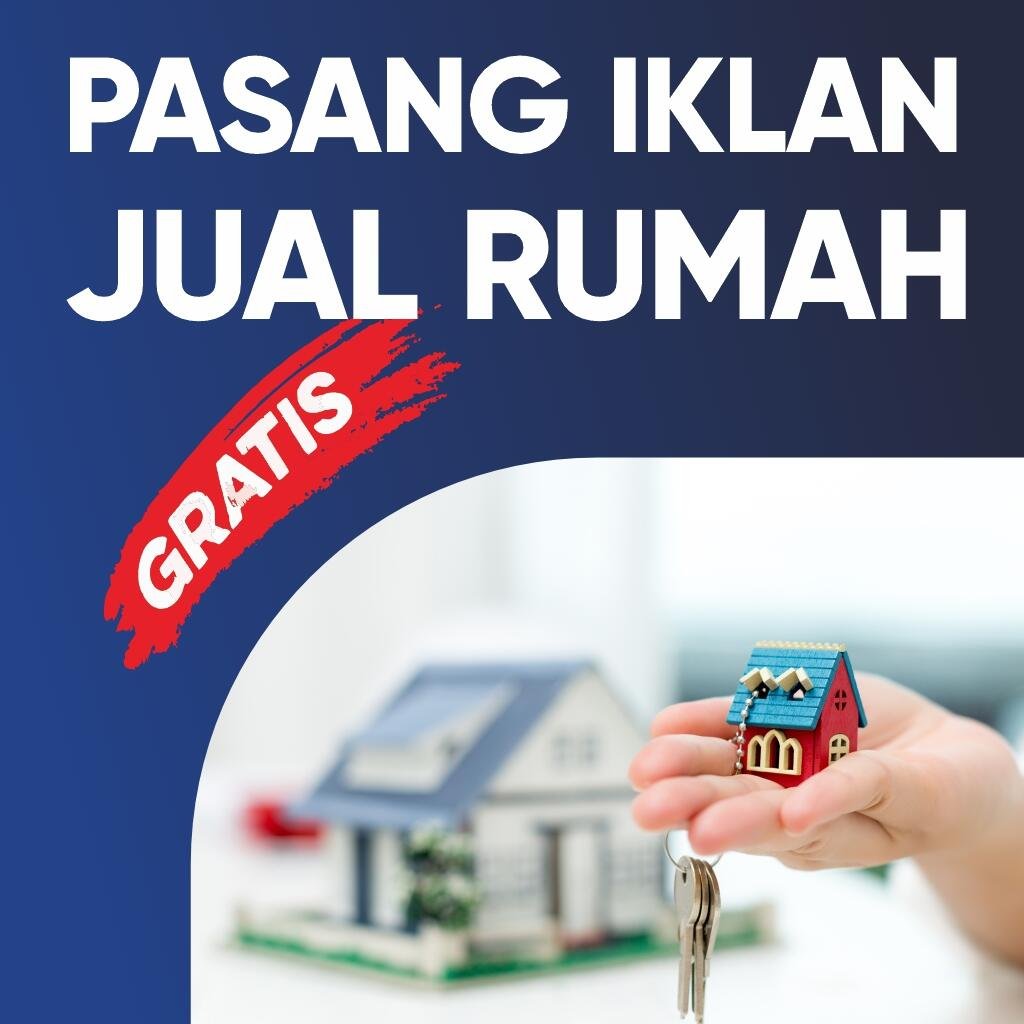Sebagai salah satu pilar ekonomi kreatif, industri film Indonesia kini mengalami tren yang cukup menarik. Meskipun teknologi dan akses produksi semakin maju, sejumlah rumah produksi tampak lebih tertarik mengulang kisah lama yang pernah sukses di masa lalu. Hal ini bisa dilihat dari sutradara Riri Riza dan produser Mira Lesmana yang berusaha melahirkan kembali kisah legendaris Ada Apa Dengan Cinta? (2002) melalui film musikal Rangga & Cinta (2025).
Meskipun hadir dengan nuansa baru dalam format musikal, film Rangga & Cinta pada dasarnya tetap mengisahkan romansa ikonik yang pernah populer di era 2000-an. Sayangnya, perubahan dalam gaya penyajian tersebut tidak diimbangi dengan pembaruan yang signifikan dalam ide cerita. Fenomena ini jelas mencerminkan kecenderungan industri film Indonesia yang tampak lebih nyaman memakai formula cerita lama daripada menciptakan narasi baru. Dalam kerangka ekonomi kreatif, strategi ini memang menawarkan potensi risiko finansial yang lebih rendah dibandingkan dengan cerita orisinal. Namun, strategi ini juga mengindikasikan ketergantungan yang berlebihan pada nostalgia dan ketakutan untuk mengambil risiko dengan cerita yang lebih segar dan berani, yang pada akhirnya dapat membatasi pertumbuhan naratif industri film itu sendiri.
Dari sisi penonton sendiri, fenomena ini kerap ditanggapi dalam dua arah. Sebagian berpendapat bahwa film seperti Rangga & Cinta adalah bukti nyata bahwa perfilman Indonesia mulai kehilangan kreativitasnya. Namun, ada pula yang menyambutnya dengan antusias karena merasa diajak bernostalgia. Bahkan, beberapa menilai bahwa menonton jenis film tersebut bukan lagi soal menikmati jalan cerita, tetapi juga kerelaan untuk membeli kenangan di bioskop. Oleh karena itu, film seperti ini sering diproduksi karena menawarkan sesuatu yang tidak bisa dibeli di tempat lain, yaitu kerinduan akan masa lalu.
Pada level yang mendalam, fenomena membeli atau menjual nostalgia melalui film dapat kita pahami melalui kacamata embeddedness, yaitu sebuah pandangan yang menyatakan bahwa tindakan ekonomi tidak hanya dipengaruhi rasionalitas saja, tetapi juga oleh hubungan sosial, budaya, atau emosional di sekitarnya. Dalam konteks ini, keputusan untuk menonton film Rangga & Cinta tidak hanya soal menukar uang dengan hiburan, tetapi juga soal keterikatan emosional penonton pada kenangan masa lalu. Nilai yang mereka kejar bukan sekadar tontonan, melainkan juga perasaan hangat yang muncul seperti rindu pada masa remaja atau memori tentang cinta pertama.
Perkembangan industri film saat ini memperlihatkan bahwa kepentingan pasar telah memengaruhi hampir semua sisi kreativitas, bahkan sampai pada hal yang bersifat personal seperti memori. Industri ini tidak lagi sekadar menjual narasi atau estetika, tetapi juga pengalaman emosional yang sengaja diciptakan untuk membangkitkan nostalgia dan mendorong penonton untuk datang ke bioskop. Dalam sosiologi ekonomi, hal ini memperlihatkan bahwa ekonomi, sosial, dan budaya tidak pernah benar-benar terpisah. Nilai sentimental yang seharusnya tumbuh dari hubungan sosial kini menjadi bagian dari mekanisme pasar, di mana nostalgia dijadikan sumber keuntungan.
Sekilas, keterikatan antara aspek ekonomi, sosial, dan budaya dalam industri film tampak wajar. Pasar memperoleh keuntungan, sementara penonton menerima hiburan. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, muncul sebuah paradoks. Ketika kepentingan ekonomi terlalu mendominasi, film yang seharusnya berfungsi sebagai medium ekspresi manusia berubah menjadi alat untuk mencari laba semata, tanpa memperdalam makna karyanya. Nilai-nilai kemanusiaan di dalam seni pun perlahan menghilang. Nostalgia dan kerinduan yang seharusnya bersifat personal justru dikemas ulang agar dapat dijual kembali di layar lebar. Pada akhirnya, film tidak lagi berfungsi sebagai ruang ekspresi, melainkan sebagai sarana untuk mengekstraksi emosi penonton demi keuntungan ekonomi.
Di samping itu, keterikatan emosional yang dahulu terbentuk secara organik antara film dan penonton kini semakin dipengaruhi oleh strategi pemasaran yang sistematis. Nostalgia tidak lagi lahir dari pengalaman bersama yang autentik, melainkan dirancang oleh algoritma media dan dinamika pasar. Penonton diarahkan untuk merasakan kerinduan terhadap momen yang mungkin tidak pernah mereka alami. Dengan cara ini, kapitalisme nostalgia bekerja secara halus, menanamkan keinginan pada penonton yang sebenarnya telah dikondisikan oleh pasar.
Kritik lain menyoroti bagaimana keterikatan sosial yang seharusnya memperkuat jaringan antarindividu justru dimanfaatkan untuk komersialisasi. Film yang dahulu berperan dalam merefleksikan kehidupan manusia kini berubah menjadi instrumen pembentuk ilusi kedekatan. Penonton dibuat seolah merasa terhubung secara emosional dengan film, padahal hubungan tersebut dibentuk secara sengaja oleh strategi komersial, bukan berasal dari pengalaman yang autentik. Tujuannya bukan lagi mengunggah empati atau refleksi, melainkan agar penonton merasa dekat dan terus mengonsumsi produk hiburan serupa. Akibatnya, ekonomi kreatif yang seharusnya melahirkan ide-ide baru kini justru kerap menjual gagasan keaslian semu lewat nostalgia yang telah diformat ulang demi memenuhi kebutuhan pasar.
Apabila fenomena ini terus berlanjut, industri perfilman berpotensi mengalami stagnasi kultural. Dunia sinema tidak lagi berfungsi sebagai ruang yang melahirkan makna baru, tetapi sekadar tempat mengulang nostalgia agar aliran modal terus berputar. Kreativitas yang seharusnya menjadi inti dari ekonomi kreatif justru terkubur oleh strategi bisnis yang suka bermain aman. Hubungan sosial dan budaya yang diharapkan dapat berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan industri justru berubah menjadi belenggu bagi perkembangan seni. Pada akhirnya, masyarakat hanya menjadi penonton dari komodifikasi ingatan mereka sendiri.
Kritik terhadap fenomena ini bukan berarti menolak nostalgia secara mentah-mentah. Namun, yang perlu disorot adalah keberanian sinema Indonesia untuk tidak terus terjebak dalam dominasi pasar yang bermain pada emosi semata. Keterikatan sosial dan budaya seharusnya bisa digunakan untuk menciptakan kisah-kisah baru yang orisinal dan reklektif. Apabila dipahami secara etis, keterikatan itu dapat mendorong sektor ekonomi kreatif ke arah yang lebih manusiawi. Film tidak lagi sekadar komoditas nostalgia, tetapi bisa menjadi ruang refleksi sosial yang memperkaya kehidupan masyarakat.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”