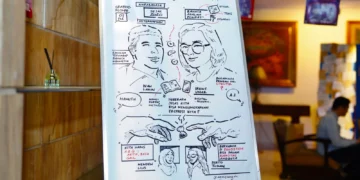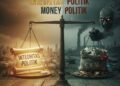Eleanor Burke Leacock (1922-1987) adalah seorang teoretikus fundamentalis dalam antropologi feminis Marxis. Sepanjang karier ilmiahnya yang produktif, perhatiannya tertuju pada dinamika hierarki sosial dalam konteks historis, dan bagaimana hasil tidak ditentukan sebelumnya, melainkan merupakan hasil dari perlawanan dan praktik emansipatoris apa pun yang muncul dalam konteks tersebut. Bagi Leacock, perjuangan-perjuangan ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berakar pada praktik sehari-hari.
Eleanor Leacock lahir di Greenwich Village dari kritikus sastra Kenneth Burke dan matematikawan Lily Batterham. Orang tuanya mendukung pendidikan dan berharap putri mereka dapat mengejar karier. Pada tahun 1939, ia mendapatkan beasiswa untuk Radcliffe dan bergabung dengan sekelompok mahasiswa progresif yang cemerlang dalam tugas akademik, meskipun dianggap tidak diterima secara sosial oleh teman-teman sekelas lainnya karena ketidakmampuan finansial, pandangan politik sosialis atau komunis, atau latar belakang Yahudi. Dalam kuliah antropologi keduanya, profesor Alfred Tozzer mengingatkan mahasiswa bahwa, jika mereka berniat untuk menjadi antropolog, mereka sebaiknya mengembangkan kemandirian, karena peluang kerja di bidang antropologi sangat sedikit. Ia mengingat saat itu berpikir dengan penuh keyakinan alih-alih marah, “Akan kubuktikan” Bersama suami pertamanya Richard Leacock, seorang mahasiswa Harvard yang memiliki minat dalam dunia film, ia pindah ke New York dan mendaftar di Barnard pada tahun 1942. Pandangan feminisnya diperkuat ketika ia ditolak untuk menjadi asisten perancang di Columbia meskipun meraih nilai tertinggi dalam kursus desain; Ia diberitahu bahwa penolakannya disebabkan oleh fakta bahwa ia seorang wanita.
Perdebatan tentang kedudukan perempuan dalam politik kerap dibingkai oleh asumsi bahwa dominasi laki-laki bersifat “alami” dan tak berubah. Eleanor Burke Leacock menantang asumsi itu dengan menunjukkan bahwa relasi gender selalu historis, terikat pada mode produksi, dan bertransformasi seiring perubahan ekonomi–politik. Kerangka ini relevan untuk membaca dinamika politik di Banda Aceh yang memiliki sejarah panjang, dari kesultanan, kolonialisme, konflik bersenjata, hingga rekonstruksi pascakonflik dan penerapan syariat.
Leacock, sebagai antropolog feminis materialis, mengkritik apa yang ia sebut “patriarki abadi” gagasan bahwa subordinasi perempuan bersifat universal lintas ruang dan waktu. Baginya, ketimpangan gender bukan fenomena ahistoris, melainkan produk formasi sosial tertentu. Dengan demikian, analisis politik perempuan menuntut pelacakan jejak perubahan struktur produksi, kepemilikan, dan otoritas yang mengkonstruksi peran gender.
Di dalam masyarakat sebelum kapitalisme, Leacock menggambarkan berbagai pola kekuasaan di mana perempuan tidak selalu memiliki posisi subordinasi yang sama. Saat kolonialisme dan kapitalisme menghadirkan pasar uang, kepemilikan tanah pribadi, serta sistem birokrasi modern, telah terjadi perubahan dalam pembagian kerja dan struktur kekuasaan dalam keluarga yang sering kali merendahkan peranan ekonomi perempuan. Pandangan ini bermanfaat untuk memahami Aceh yang mengalami perubahan dalam struktur ekonomi dari sistem perdagangan maritim, perjanjian kolonial, konflik, hingga ekonomi jasa dan konstruksi setelah tsunami.
Banda Aceh memiliki latar belakang politik yang khas. Di abad ke-17, Aceh dipimpin oleh empat ratu. Ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap politik perempuan bukanlah sesuatu yang tidak mungkin dalam tradisi setempat. Namun, keberadaan ratu tidak selalu mencerminkan kesetaraan struktural; yang lebih krusial adalah sejauh mana lembaga dan ekonomi pada masa itu memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berperan dalam pemerintahan dan patronase.
Studi sejarah tentang sultanah Aceh menunjukkan bahwa otoritas perempuan kala itu berkelindan dengan diplomasi, perdagangan internasional, dan jaringan ulama. Ini mempertegas tesis Leacock: posisi perempuan tidak berdiri sendirian, melainkan terkait erat dengan relasi produksi dan arus kekuasaan. Membaca Banda Aceh lewat lensa ini menghindarkan kita dari romantisasi masa lalu sekaligus dari klaim “patriarki abadi”.
Studi sejarah tentang sultanah Aceh menunjukkan bahwa otoritas perempuan kala itu berkelindan dengan diplomasi, perdagangan internasional, dan jaringan ulama. Ini mempertegas tesis Leacock: posisi perempuan tidak berdiri sendirian, melainkan terkait erat dengan relasi produksi dan arus kekuasaan. Membaca Banda Aceh lewat lensa ini menghindarkan kita dari romantisasi masa lalu sekaligus dari klaim “patriarki abadi”.
Perempuan di Banda Aceh juga hadir kuat dalam organisasi keagamaan dan lembaga pendidikan. Ini menyediakan modal simbolik dan jaringan. Namun, translasi modal itu menjadi kapital politik elektoral tidak otomatis. Perlu infrastruktur kampanye, konsultan, relawan, dan dana. Di sinilah analisis materialis Leacock menambah ketajaman atas dimensi “biaya” politik.
Aktivisme perempuan melalui LSM lokal misalnya advokasi hukum, layanan korban kekerasan, dan pendidikan politik berperan sebagai “sekolah politik” yang membekali keterampilan dan jejaring. Tetapi keberlanjutan organisasi bergantung pada pendanaan proyek. Ketika siklus donor berubah, kapasitas kaderisasi pun terdampak. Ini menunjukkan keterikatan erat antara ekonomi pendanaan dan produksi aktor politik.
Dalam ruang kebijakan, isu yang sering diadvokasi perempuan meliputi layanan publik, kesehatan ibu anak, perlindungan kekerasan berbasis gender, dan pekerjaan layak. Ketika perempuan berhasil menembus lembaga legislatif, fokus isu tersebut memperkaya agenda politik lokal. Namun, resistensi dapat muncul jika dianggap “isu privat”. Leacock menolak dikotomi privat–publik yang menyingkirkan kerja reproduktif dari politik.
Kerangka Leacock juga relevan untuk membaca perubahan generasi. Generasi muda digital native menciptakan kanal partisipasi baru melalui platform daring, crowdfunding, dan micro-volunteering. Ini mengurangi hambatan masuk karena sebagian logistik bisa didistribusikan. Namun, ketimpangan akses teknologi dan literasi digital tetap perlu diperhitungkan.
Secara normatif, tujuan melampaui “patriarki abadi” bukan sekadar menambah jumlah perempuan di kursi politik, melainkan mentransformasikan struktur yang mereproduksi ketimpangan: pembagian kerja, kontrol sumber daya, dan tata kelola partai. Ketika basis material berubah, peluang lahirnya norma politik yang lebih setara meningkat.
Dalam konteks Banda Aceh, kebijakan kota yang berperspektif gender dari perencanaan ruang, keselamatan jalan, hingga layanan usaha mikro dapat menjadi lokomotif yang mendorong budaya politik inklusif. Politik yang berhasil adalah yang menghubungkan nilai-nilai lokal dengan inovasi kebijakan yang terukur dampaknya pada kesejahteraan warga.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”